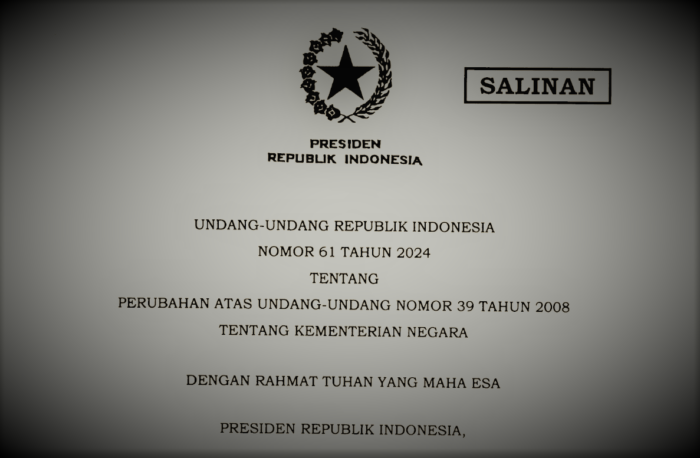PortalMadura.com – Di sebuah negeri yang katanya menjunjung demokrasi, kita kerap bertanya, di manakah ujung dari kekuasaan dan di mana batas dari keberhasilan? Tentu, ini bukan sebuah perkara yang sederhana, terlebih ketika menyangkut persoalan organisasi pemerintahan. Negara, dengan segala kerumitan dan persoalan multidimensionalnya, memang memerlukan tangan-tangan terampil yang mampu menavigasi rimba persoalan. Namun, apakah sebuah kabinet dengan 34 menteri, yang menjulang bak barisan gunung tinggi, benar-benar efektif?
Ini adalah pertanyaan yang merangsek ke inti persoalan manajemen negara, di mana kuantitas terkadang berbalik mengkhianati kualitas. Sebuah kabinet besar, dalam sejarahnya, kerap kali dihubungkan dengan niat politis untuk merangkul sebanyak mungkin pihak, bukan demi pemerintahan yang efisien, melainkan demi stabilitas politik. Sehingga, tak jarang kabinet yang gemuk adalah wujud dari politicking: penguasa yang berupaya membagi-bagi kursi sebagai kompromi politik dengan lawan-lawan politiknya, demi memuluskan jalannya. Namun, apakah ini setara dengan keberhasilan atau malah menghambat efektivitas?
Dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyebutkan tidak ada batasan jumlah menteri (selama dibutuhkan boleh-boleh saja menambah atau mengurangi), agak-agaknya, sebentar lagi Indonesia akan memiliki 34 kementerian dalam kabinet ke depannya (sebagaimana isu yang beredar), yang akan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat: dari ekonomi, sosial, politik, hingga kebudayaan. Dengan segala kecanggihan birokrasi yang diklaim, apakah kita mampu mengatakan bahwa jumlah sebesar itu benar-benar efektif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang kian kompleks?
Efektivitas, Di Manakah Itu?
Dalam buku The Rise and Fall of Nations karya Ruchir Sharma, penulis mengungkapkan bahwa negara-negara yang sukses secara ekonomi dan politik cenderung memiliki kabinet yang ramping dan berfokus pada tugas-tugas utama. Negara seperti Singapura, misalnya, yang secara geografis kecil tetapi memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang besar, beroperasi dengan kabinet yang relatif ramping. Di sini, argumen bahwa lebih sedikit lebih baik dalam konteks pemerintahan mulai muncul. Mengapa? Karena struktur yang lebih sederhana memungkinkan kontrol dan pengawasan yang lebih mudah serta kebijakan yang lebih koheren.
Namun, kita juga tak bisa menutup mata pada realitas lain. Indonesia, sebuah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan wilayah yang terfragmentasi menjadi ribuan pulau, tentu membutuhkan manajemen yang rumit. Ada nuansa di mana pemerintahan memerlukan lebih banyak otoritas untuk menangani setiap sektor secara terperinci. Tapi, di titik inilah kita berhadapan dengan dilema: lebih banyak kementerian berarti lebih banyak birokrasi, dan lebih banyak birokrasi sering kali berarti lebih banyak peluang untuk ketidakberesan.
Mungkin sudah saatnya kita bertanya, seberapa besar kabinet yang benar-benar dibutuhkan untuk mengelola sebuah bangsa yang luas dan majemuk seperti Indonesia? Apakah betul bahwa setiap kementerian yang ada saat ini memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat? Atau, jangan-jangan sebagian besar dari mereka hanya menjadi pelengkap politik dari kekuasaan yang kerap kali terjebak dalam permainan bagi-bagi kursi?
Lintas Birokrasi, Lintas Batas Rasionalitas
Kalau kita tarik benang lebih jauh, kabinet besar tak hanya memunculkan masalah dari segi politik, tapi juga menyentuh perbatasan ekonomi dan sosial. Semakin besar sebuah kabinet, semakin banyak pula anggaran yang dibutuhkan untuk operasionalisasi kementerian tersebut. Dalam sebuah kajian yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Indonesia, setiap kementerian memiliki alokasi anggaran yang cukup besar untuk menyokong gaji pegawai, tunjangan, hingga operasionalisasi sehari-hari. Ini semua tentu berasal dari kantong negara—kantong yang seharusnya diutamakan untuk rakyat, tetapi lebih banyak habis untuk menopang struktur birokrasi yang terkadang gemuk tanpa alasan.
Apakah kita pernah berpikir, berapa banyak sekolah yang bisa dibangun atau fasilitas kesehatan yang bisa diperbaiki dengan anggaran yang digunakan untuk menopang birokrasi ini? Ada semacam paradoks yang terjadi di sini. Di satu sisi, pemerintah selalu menyerukan efisiensi dalam berbagai sektor, terutama di sektor publik. Tetapi di sisi lain, kita melihat bahwa struktur birokrasi yang ada justru semakin membesar tanpa ada penjelasan jelas mengenai urgensi di baliknya.
Dalam pandangan filsuf politik seperti Max Weber, birokrasi memang sebuah keharusan dalam sebuah negara modern. Namun, Weber juga menekankan bahwa birokrasi haruslah efisien dan terfokus. Struktur yang besar dan gemuk hanya akan mengakibatkan birokratisasi yang berlebihan, di mana setiap keputusan akan memerlukan persetujuan berlapis-lapis hingga akhirnya kehilangan momentum. Pada titik ini, kita tak hanya kehilangan waktu, tetapi juga kesempatan untuk merespons perubahan yang cepat terjadi di dunia global.
Jika kita renungkan lebih dalam, persoalan kabinet gemuk bukan hanya tentang kuantitas, tetapi juga kualitas. Jumlah menteri yang besar tak serta-merta menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif. Kerap kali, sebaliknya yang terjadi. Sejumlah studi menunjukkan bahwa negara-negara dengan kabinet kecil cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal manajemen krisis dan kebijakan ekonomi. Jerman, sebagai contoh, mampu mengatasi krisis keuangan global dengan kabinet yang relatif kecil, tetapi sangat efisien dalam hal pengambilan keputusan.
Politisasi atau Profesionalisasi?
Dalam kajian politik, kabinet besar kerap dihubungkan dengan kompromi politik. Setiap kali sebuah pemilu selesai, pemerintah baru terbentuk dengan susunan kabinet yang, secara ironis, tak jarang dipenuhi oleh orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang partai. Alhasil, profesionalisme menjadi taruhannya. Jabatan menteri sering kali diberikan bukan berdasarkan kompetensi, melainkan sebagai ‘imbalan’ politik bagi para tokoh atau kelompok yang telah mendukung kandidat pemenang.
Di sinilah kita bertemu dengan problem yang lebih mendalam. Alih-alih membangun sebuah kabinet yang berisi para ahli di bidangnya, kita justru melihat fenomena di mana jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan diisi oleh orang-orang yang tak selalu memiliki kapasitas atau keahlian di bidang tersebut. Dalam kasus Indonesia, kabinet yang besar ini kerap kali menimbulkan pertanyaan tentang urgensi dan kompetensi para menterinya. Apakah mereka benar-benar dipilih karena keahlian yang mumpuni, atau hanya karena afiliasi politik yang menguntungkan?
Hal ini tentu menimbulkan dampak yang besar terhadap jalannya pemerintahan. Ketika sebuah kementerian dipimpin oleh orang yang kurang memahami esensi tugas dan tanggung jawabnya, kebijakan yang dihasilkan pun cenderung tak efektif. Bukan hanya itu, koordinasi antar kementerian juga menjadi lebih rumit, terutama ketika terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang. Misalnya, dalam urusan lingkungan hidup, sering kali terjadi perbedaan pandangan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pertanian. Dalam kondisi ini, bukannya solusi yang dihasilkan, melainkan konflik birokrasi yang berkepanjangan.
Filsafat Politik dan Budaya Kekuasaan
Jika kita kembali menengok ke dalam filsafat politik, ada sebuah konsep yang menarik dari Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan tentang bagaimana negara harus dikelola. Menurut Hobbes, negara yang kuat adalah negara yang mampu mengonsolidasikan kekuasaannya dalam satu entitas yang efektif, bukan dalam struktur yang berlapis-lapis dan penuh dengan kompromi. Dalam hal ini, Hobbes seolah-olah menyiratkan bahwa ukuran dan efisiensi adalah kunci dari keberhasilan sebuah pemerintahan. Negara yang terlalu besar, dalam artian struktur dan birokrasi, justru akan kehilangan kendali atas rakyatnya.
Namun, realitas politik modern justru menunjukkan arah yang sebaliknya. Struktur kekuasaan sering kali dibagi-bagi untuk menjaga keseimbangan politik, bukan efisiensi. Dalam konteks Indonesia, pembagian kursi menteri sering kali dilakukan untuk merangkul berbagai kekuatan politik yang berbeda. Dalam jangka pendek, ini mungkin berhasil menjaga stabilitas politik. Tetapi dalam jangka panjang, kita perlu bertanya, apakah stabilitas ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat, atau hanya sekadar untuk melanggengkan kekuasaan? Apakah kita benar-benar membutuhkan 34 kementerian untuk mengelola negara ini, atau cukup dengan kabinet kecil yang berisi para profesional dan teknokrat yang kompeten?
Pada akhirnya, persoalan kabinet yang gemuk ini hanya bisa diselesaikan oleh pemimpin yang berani melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Ini bukan sekadar tentang mengurangi jumlah kementerian atau memangkas anggaran, tetapi juga tentang mengubah pola pikir dan budaya kekuasaan yang selama ini melekat dalam politik Indonesia. Kita butuh pemimpin yang berani mengambil risiko untuk menciptakan kabinet yang kecil tetapi solid, yang mampu bekerja dengan efisien dan profesional tanpa harus terjebak dalam permainan politik yang berkepanjangan.
Namun, apakah pemimpin seperti itu ada di tengah kita? Apakah ada sosok yang mampu melepaskan diri dari jerat politicking dan benar-benar berfokus pada pembangunan bangsa? Jawaban dari pertanyaan ini mungkin masih menggantung, tetapi satu hal yang pasti, kita tak bisa terus-menerus berada dalam struktur pemerintahan yang gemuk tanpa hasil yang signifikan. Jika tak segera diatasi, ini hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat, sementara para elite politik terus bermain-main dengan kekuasaan mereka.
Di satu sisi, rakyat yang digembar-gemborkan sebagai pemilik kedaulatan sejatinya justru terpinggirkan dari percaturan. Apalagi, dalam sistem politik Indonesia yang menganut demokrasi perwakilan, rakyat memang hanya berperan dalam proses elektoral setiap lima tahun sekali, setelah itu suara mereka seolah-olah hilang ditelan janji-janji manis yang tak terealisasi. Kabinet yang gemuk hanya memperpanjang rantai keterasingan rakyat dari pemerintahannya. Dari lapisan menteri hingga jajaran birokrat di bawahnya, komunikasi dan aspirasi sering kali tersumbat oleh tumpukan kepentingan pribadi dan kelompok yang sudah tertanam begitu dalam dalam kultur kekuasaan Indonesia.
Birokrasi yang Lambat, Masyarakat yang Terkorbankan
Jika kita berpaling sejenak dari keriuhan politik kabinet, kita akan melihat dampak langsung dari birokrasi yang besar terhadap pelayanan publik. Salah satu contoh konkret adalah layanan kesehatan dan pendidikan, dua pilar utama yang seharusnya menjadi prioritas pemerintahan yang peduli pada kesejahteraan rakyatnya. Namun, dengan struktur pemerintahan yang gemuk, kebijakan sering kali kehilangan fokus dan implementasi di lapangan terganggu oleh birokrasi yang lambat.
Dalam banyak kasus, masyarakat yang membutuhkan layanan publik—seperti perawatan medis atau akses pendidikan berkualitas—justru sering kali dihadapkan pada prosedur yang berbelit-belit. Sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan layanan langsung kepada masyarakat kerap kali habis di meja-meja birokrat yang hanya menambah tumpukan administrasi tanpa solusi nyata. Di sini, kita melihat bagaimana kabinet yang besar justru menciptakan inefisiensi yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa birokrasi di Indonesia cenderung lambat. Keputusan yang seharusnya cepat diambil kerap tertunda karena banyaknya jalur yang harus ditempuh. Apalagi dengan adanya kementerian yang tumpang tindih, proses pengambilan keputusan semakin panjang dan berbelit. Pada akhirnya, masyarakat yang menjadi korban, sementara para pemimpin sibuk dengan urusan politik mereka.
Ketika Birokrasi Menghambat
Krisis pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak 2020 menjadi contoh nyata betapa birokrasi yang besar dan tidak efisien justru menjadi penghambat dalam menangani keadaan darurat. Dalam kasus Indonesia, respons pemerintah terhadap krisis kesehatan global ini sempat terseok-seok di awal. Meskipun pemerintah pusat mengumumkan berbagai kebijakan, pelaksanaan di lapangan sering kali kacau. Salah satu alasan utama dari ketidakefisienan ini adalah koordinasi yang buruk antar lembaga dan kementerian.
Ketika krisis melanda, kecepatan dan ketepatan adalah kunci. Negara-negara yang berhasil menangani pandemi dengan baik adalah mereka yang mampu merespons dengan cepat dan tepat. Korea Selatan, misalnya, berhasil mengendalikan penyebaran virus dengan strategi yang terkoordinasi dengan baik antara berbagai sektor pemerintahan, meskipun mereka memiliki struktur pemerintahan yang jauh lebih ramping dibandingkan Indonesia.
Sebaliknya, di Indonesia, koordinasi antar kementerian dan lembaga sering kali tumpang tindih. Setiap kementerian berusaha menonjolkan perannya sendiri-sendiri, tanpa sinergi yang jelas. Akibatnya, penanganan pandemi yang seharusnya bersifat menyeluruh dan terfokus menjadi terpecah-pecah. Bukan hanya sektor kesehatan yang terkena dampaknya, tetapi juga sektor ekonomi, sosial, dan pendidikan.
Ini mengingatkan kita pada kata-kata Jean-Paul Sartre dalam Being and Nothingness, bahwa manusia sering kali terjebak dalam ilusi kebebasan. Kita pikir dengan memperbanyak pilihan—dalam hal ini memperbanyak kementerian—kita akan lebih bebas dan lebih efektif. Namun, dalam kenyataannya, semakin banyak pilihan sering kali hanya membuat kita semakin terjebak dalam ketidakpastian dan kekacauan.
Dualitas Politik dan Kebudayaan
Jika kita melihat lebih dalam, ada sebuah dualitas menarik yang terjadi dalam politik Indonesia. Di satu sisi, kita sering berbicara tentang modernitas, kemajuan, dan pembangunan nasional. Namun, di sisi lain, kita tetap terjebak dalam pola-pola politik lama yang berfokus pada kompromi kekuasaan dan distribusi jabatan untuk meredam konflik antar elit. Dalam konteks ini, kabinet yang besar adalah cerminan dari budaya politik yang belum sepenuhnya beranjak dari masa lalu, masa di mana stabilitas politik lebih diutamakan daripada efisiensi pemerintahan.
Pergesekan antara budaya politik tradisional yang berorientasi pada patronase dan cita-cita modernitas yang mengutamakan transparansi dan efisiensi inilah yang menciptakan kontradiksi dalam tubuh pemerintahan. Kabinet besar bukan hanya masalah manajemen kekuasaan, tetapi juga cerminan dari budaya kekuasaan yang masih enggan melepaskan diri dari belenggu masa lalu. Seolah-olah kita masih hidup di zaman kerajaan, di mana loyalitas kepada raja atau penguasa adalah yang utama, sementara kepentingan rakyat menjadi sekadar nomor dua.
Mungkin inilah yang membuat kita bertanya-tanya, apakah reformasi politik yang selama ini didengungkan benar-benar telah tercapai? Apakah kita benar-benar telah bertransformasi menjadi sebuah negara modern yang mengutamakan efisiensi dan transparansi, ataukah kita hanya berganti baju, sementara struktur kekuasaan tetap sama?
Masyarakat yang Cemas, Pemimpin yang Alergi Kritik
Di tengah masyarakat yang kian kritis, harapan akan pemerintahan yang bersih dan efisien semakin besar. Namun, alih-alih merespons dengan reformasi yang nyata, pemerintah sering kali justru bersikap defensif dan alergi terhadap kritik. Sikap ini, jika kita telusuri, tak lepas dari karakteristik kekuasaan itu sendiri. Dalam pandangan Michel Foucault, kekuasaan selalu cenderung untuk mempertahankan dirinya. Kekuasaan tidak akan pernah melepaskan kendalinya dengan mudah, dan dalam banyak kasus, ia justru akan berupaya menekan setiap bentuk kritik atau resistensi yang muncul dari masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat jelas dalam bagaimana pemerintah sering kali merespons kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak efektif. Kritik terhadap birokrasi yang gemuk dan lambat sering kali dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai masukan konstruktif. Padahal, di negara-negara demokratis yang sehat, kritik dari masyarakat justru menjadi salah satu mekanisme penting untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
Namun, kita juga harus menyadari bahwa masyarakat yang kritis sering kali berhadapan dengan struktur kekuasaan yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Dalam hal ini, kita kembali pada masalah mendasar: kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat kabinet. Keputusan-keputusan penting yang berdampak luas terhadap kehidupan rakyat sering kali diambil tanpa melibatkan partisipasi publik secara nyata. Di sinilah letak permasalahannya: bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam proses politik jika mereka tidak diberi akses untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam pemerintahan?
Pemerintahan Ideal
Di titik ini, kita perlu merenung: apakah kita akan terus terjebak dalam pola-pola lama, ataukah kita akan berani untuk melakukan perubahan mendasar? Kabinet yang gemuk bukanlah jawaban atas tantangan-tantangan besar yang dihadapi bangsa ini. Yang kita butuhkan adalah pemerintahan yang ramping, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Kita membutuhkan para pemimpin yang berani melakukan reformasi birokrasi, bukan sekadar untuk memenuhi janji politik, tetapi demi masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Pemerintahan yang ideal bukanlah pemerintahan yang dipenuhi dengan kompromi politik dan jabatan-jabatan yang dibagi-bagi demi meredam konflik antar elit. Pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang berani mengambil keputusan sulit demi kebaikan bersama. Kita membutuhkan pemimpin yang berani memangkas birokrasi yang berlebihan, mengurangi jumlah kementerian yang tidak efektif, dan memilih para profesional yang benar-benar memahami tugas dan tanggung jawab mereka.
Pada akhirnya, reformasi kabinet bukanlah sekadar masalah teknis birokrasi, tetapi juga menyangkut persoalan moral dan etika dalam politik. Kita butuh pemimpin yang memiliki keberanian moral untuk melepaskan diri dari pola-pola lama yang hanya menguntungkan segelintir elit, dan berfokus pada pelayanan publik yang efektif dan transparan.
Persimpangan Jalan
Masyarakat Indonesia kini berada pada persimpangan jalan. Di satu sisi, ada keinginan besar untuk perubahan, untuk pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih efisien. Di sisi lain, kita masih terjebak dalam struktur politik dan birokrasi yang kaku dan tidak fleksibel. Kabinet yang besar hanya mempertebal lapisan-lapisan birokrasi yang memisahkan rakyat dari pemimpinnya. Jika kita ingin maju sebagai bangsa, kita harus berani melakukan perubahan.
Apakah kita siap untuk menjalani jalan yang lebih sulit tetapi membawa perubahan yang nyata? Ataukah kita akan terus bertahan dalam kenyamanan yang palsu, yang hanya menunda krisis yang lebih besar di masa depan?
Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin belum bisa dijawab sekarang, tetapi satu hal yang pasti: pertanyaan-pertanyaan ini harus terus kita gumulkan, renungkan, dan bicarakan secara terbuka. Sebab, masa depan bangsa ini tidak bisa hanya ditentukan oleh segelintir elit politik di balik pintu tertutup. Ini adalah masa depan yang harus diperjuangkan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab kita terhadap generasi yang akan datang.
Kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan berharap pada keajaiban. Perubahan tidak akan datang dengan sendirinya, apalagi jika kita terus terjebak dalam logika politik transaksional yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Di sinilah letak pentingnya peran masyarakat sipil, aktivis, dan intelektual publik untuk terus memberikan tekanan, kritik, dan dorongan kepada pemerintah agar reformasi birokrasi yang sejati dapat terwujud.
Dalam konteks ini, kritik terhadap kabinet yang besar bukanlah sekadar kritik teknis tentang ukuran pemerintahan, tetapi juga kritik terhadap arah dan filosofi politik kita. Apakah kita ingin terus mempertahankan politik kompromi yang mengorbankan efisiensi demi stabilitas semu, ataukah kita siap untuk menghadapi ketidaknyamanan sementara demi menciptakan pemerintahan yang lebih baik?
Di titik inilah, kita perlu mengingat kembali apa yang pernah dikatakan oleh pemikir Italia, Antonio Gramsci: “Krisis terjadi ketika yang lama sudah mati, tetapi yang baru belum lahir.” Indonesia, dengan segala potensi dan tantangannya, mungkin sedang berada di tengah-tengah krisis semacam itu. Kita merasakan bahwa cara-cara lama sudah tidak efektif lagi, tetapi kita belum sepenuhnya menemukan jalan baru yang bisa membawa kita ke masa depan yang lebih baik.
Mari Tinjau
Namun, penting untuk diingat bahwa kritik yang baik bukan hanya menawarkan keluhan, tetapi juga solusi. Jika kita sepakat bahwa kabinet yang besar bukanlah solusi yang tepat untuk Indonesia, maka kita harus mulai membayangkan seperti apa pemerintahan yang lebih ideal. Pertama-tama, kita perlu meninjau ulang fungsi dan peran setiap kementerian. Apakah semua kementerian yang ada saat ini benar-benar diperlukan? Apakah tidak ada kementerian yang fungsinya bisa digabungkan atau dihapus sama sekali?
Selain itu, kita perlu memikirkan mekanisme pemilihan menteri yang lebih transparan dan berbasis meritokrasi. Dalam situasi politik yang penuh dengan kompromi, sering kali pemilihan menteri didasarkan pada pertimbangan politik semata, tanpa memperhatikan apakah kandidat tersebut benar-benar kompeten dalam bidangnya. Kita membutuhkan sistem yang memastikan bahwa setiap menteri yang diangkat adalah orang yang benar-benar memiliki kapasitas untuk memimpin kementeriannya dengan baik.
Di negara-negara maju, proses seleksi menteri sering kali melibatkan uji kelayakan yang ketat, baik melalui mekanisme parlemen maupun lembaga independen. Indonesia bisa belajar dari praktik-praktik ini. Dengan uji kelayakan yang terbuka dan transparan, kita bisa memastikan bahwa mereka yang duduk di kursi menteri bukanlah orang-orang yang hanya sekadar mendapatkan “jatah” politik, tetapi benar-benar memiliki keahlian dan dedikasi untuk melayani publik.
Kedua, kita juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kinerja menteri dan kementerian. Saat ini, mekanisme pengawasan sering kali lemah, dan jika ada pun, sifatnya lebih politis daripada substansial. Kita memerlukan mekanisme pengawasan yang lebih independen dan berbasis pada kinerja yang terukur. Misalnya, setiap kementerian harus memiliki target yang jelas dan terukur, serta dievaluasi secara rutin oleh badan independen. Jika seorang menteri tidak berhasil mencapai target-target tersebut, maka sudah sewajarnya mereka diganti.
Efisiensi Bukan Mimpi
Banyak negara di dunia yang telah berhasil membangun pemerintahan yang efisien dengan kabinet yang ramping. Negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Swedia, dan Denmark, misalnya, sering kali menjadi contoh bagaimana pemerintahan yang kecil bisa sangat efektif dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Dengan struktur kabinet yang tidak terlalu besar, mereka mampu bergerak cepat dalam menghadapi tantangan-tantangan global, mulai dari perubahan iklim hingga krisis migrasi.
Di negara-negara ini, jumlah kementerian memang tidak banyak, tetapi setiap kementerian bekerja dengan efisien dan memiliki wewenang yang jelas. Tidak ada tumpang tindih kebijakan, dan birokrasi diatur sedemikian rupa sehingga proses pengambilan keputusan bisa berjalan cepat. Apa yang kita lihat di sini adalah keberanian untuk memangkas struktur birokrasi yang berlebihan dan fokus pada esensi pemerintahan, yaitu melayani rakyat.
Indonesia tentu memiliki tantangan yang berbeda, tetapi itu bukan alasan untuk tidak berusaha mencapai efisiensi yang sama. Kita perlu belajar dari negara-negara yang telah berhasil membangun pemerintahan yang efisien, sambil tetap menyesuaikan dengan konteks dan karakteristik Indonesia. Jangan sampai alasan kompleksitas dan keberagaman kita dijadikan alasan untuk mempertahankan birokrasi yang gemuk dan tidak efisien.
Pada akhirnya, esensi dari kritik terhadap kabinet besar adalah tentang bagaimana kita memaknai politik itu sendiri. Politik, dalam pengertian idealnya, adalah tentang memperjuangkan kepentingan rakyat dan membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Namun, ketika politik hanya menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan di antara elit, maka esensi tersebut hilang. Politik menjadi sekadar permainan kekuasaan yang tidak memiliki makna substantif bagi kehidupan masyarakat luas.
Seorang filsuf politik kontemporer, Chantal Mouffe, pernah mengatakan bahwa politik yang sejati adalah politik yang selalu melibatkan pertarungan gagasan dan nilai-nilai. Politik bukan hanya soal negosiasi di antara elit, tetapi juga soal perjuangan ideologis untuk menentukan arah masa depan sebuah bangsa. Dalam konteks Indonesia, kita harus berani menghadapi pertarungan ini. Kita harus berani mempertanyakan apakah politik kita saat ini benar-benar melayani kepentingan rakyat, ataukah hanya melayani kepentingan segelintir elit?
Kita perlu merebut kembali makna politik yang sejati. Politik harus kembali menjadi arena di mana rakyat bisa berpartisipasi secara aktif, bukan hanya sebagai penonton pasif yang menyaksikan permainan elit. Politik harus menjadi sarana untuk memperjuangkan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan demokrasi yang substansial. Dalam hal ini, kabinet yang ramping dan efisien hanyalah langkah awal untuk mencapai tujuan yang lebih besar: menciptakan pemerintahan yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.
Membangun pemerintahan yang ideal tentu bukan perkara mudah. Dibutuhkan keberanian, dedikasi, dan komitmen dari semua pihak, baik dari elit politik maupun masyarakat sipil. Namun, jika kita benar-benar ingin melihat perubahan yang nyata, maka kita harus siap untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan, betapapun sulitnya.
Masyarakat Indonesia memiliki harapan besar terhadap pemerintahan yang lebih baik. Harapan ini tidak boleh dikhianati oleh mereka yang berada di kursi kekuasaan. Kita perlu terus mengingatkan diri bahwa pemerintahan yang besar bukanlah solusi, melainkan masalah. Pemerintahan yang efektif bukanlah pemerintahan yang dipenuhi dengan jabatan-jabatan politis, melainkan pemerintahan yang didorong oleh profesionalisme, transparansi, dan dedikasi untuk melayani rakyat.
Pada akhirnya, masa depan bangsa ini ada di tangan kita semua. Apakah kita akan terus terjebak dalam pola-pola lama yang hanya memperkuat oligarki dan birokrasi yang lambat? Ataukah kita akan bangkit dan memperjuangkan pemerintahan yang lebih ramping, lebih efektif, dan lebih demokratis? Pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang tidak hanya datang dari mulut para elit politik, tetapi dari seluruh rakyat Indonesia yang mendambakan perubahan.***